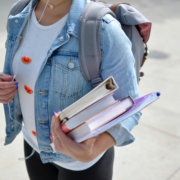Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Membeli CWLS
Rubrik Iqtishodia Republika, Jumat 23 Februari 2024
Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Membeli CWLS
Hasil dari CWLS Retail akan digunakan untuk mendanai berbagai proyek sosial yang beragam.
M Bintang Awangsyah, Ranti Wiliasih
Wakaf memiliki peran penting dalam perekonomian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2001, wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara abadi atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.
Wakaf menjadi instrumen penting yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui konsep elemen ukhuwah (persaudaraan), birr (kebajikan), dan ihsan (kebaikan) (Nisa 2017). Selanjutnya, dalam evolusi penerapan wakaf, instrumen wakaf berkembang menjadi wakaf produktif, termasuk di dalamnya wakaf uang yang dikenal sebagai wakaf produktif yang bersifat fleksibel.
Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2022, wakaf uang dapat berbentuk uang tunai atau surat berharga, dengan nilai pokok yang dijaga agar tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan. Ini merupakan langkah penting dalam memperluas penggunaan wakaf dalam mendukung kegiatan ekonomi syariah dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.
Dalam upaya mewujudkan program wakaf yang produktif, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengembangkan instrumen wakaf yang baru, dikenal sebagai Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).
CWLS retail merupakan subprogram yang dapat diikuti oleh individu, yaitu dengan jumlah minimum pemesanan satu juta rupiah. CWLS juga merupakan bentuk investasi sosial di mana wakaf uang yang terkumpul oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai nazhir melalui kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), akan dikelola dan ditempatkan dalam instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kemenkeu.
Hasil dari CWLS Retail akan digunakan untuk mendanai berbagai proyek sosial yang beragam, seperti pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), program kesehatan, pemberian beasiswa pendidikan, pengembangan hunian yang baik (wakaf hunian hasanah), penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga medis, serta pembiayaan pengobatan bagi kalangan dhuafa. Semua ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas.
Peluncuran CWLS pertama kali dilakukan pada 14 Oktober 2018 dan seri pertamanya berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 50,84 miliar. Proses ini memakan waktu sekitar 1,5 tahun hingga diterbitkan pada 10 Maret 2020. Kemudian, pembelian berikutnya dalam CWLS seri SWR001 berhasil menghimpun dana sebesar Rp 14,91 miliar pada 24 November 2020.
Namun, dengan potensi yang seharusnya lebih besar, perolehan dana dari CWLS masih tergolong rendah. Penting untuk dicatat bahwa pada 24 November 2020, dana wakaf dari CWLS retail seri SWR001 telah berhasil terkumpul dengan jumlah sekitar Rp 14,91 miliar, yang berasal dari kontribusi dari 1.041 wakif.
Capaian itu berasal dari pesanan yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, melibatkan pemesan dari 27 provinsi di seluruh negeri. Dari seluruh provinsi, DKI Jakarta terlihat sebagai salah satu yang paling berkontribusi, dengan jumlah pemesanan terbesar sebesar Rp 6,28 miliar.
Namun, berdasarkan (BWI 2020) Indeks Literasi Wakaf (ILW) DKI Jakarta merupakan ketiga terendah dengan skor 36,71 poin. Bahkan, Indeks Literasi Wakaf (ILW) DKI Jakarta masih lebih rendah diandingkan beberapa daerah dengan populasi mayoritas non-Muslim, seperti provinsi Papua yang memiliki skor 64,04 poin dan provinsi Bali dengan skor 62,49 (BWI 2020).
Pertanyaannya apakah literasi tidak berpengaruh terhadap pembelian sukuk? Untuk membuktikan ini dilakukan penelitian di DKI Jakarta, yaitu melihat pengaruh literasi terhadap intensi membeli sukuk. Responden penelitian adalah mereka yang beragama Islam, berdomisili atau tinggal di DKI Jakarta, belum pernah membeli Cash Waqf Linked Sukuk dan mengetahui/pernah mendengar Cash Waqf Linked Sukuk.
Berdasarkan hasil studi yang dilakukan disimpulkan bahwa variabel literasi wakaf dasar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi untuk membeli Cash Waqf Linked Sukuk. Mujakir dan Hidayatulloh (2022) menyimpulkan bahwa literasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang.
Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Osman (2012) yang menemukan bahwa literasi memainkan peran penting dalam memotivasi individu untuk berwakaf. Akan tetapi, hasil yang berbeda ditemukan pada hubungan antara literasi wakaf lanjutan dan intensi untuk membeli Cash Waqf Linked Sukuk.
Literasi wakaf lanjutan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi pembelian. Penjelasan ini sejalan dengan laporan survei literasi wakaf nasional yang menempatkan Provinsi DKI Jakarta pada peringkat ke-28 dalam indeks literasi wakaf lanjutan dengan skor 30.36, yang berada dalam kategori rendah.
Meskipun DKI Jakarta merupakan pemesan CWLS retail terbesar, data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan ketimpangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di provinsi ini. Secara umum, literasi keuangan di DKI Jakarta mencapai 52,99 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 96,62 persen. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa masyarakat DKI Jakarta sudah lebih banyak yang melek investasi atau survei literasi keuangan tidak mewakili populasi yang sebenarnya.